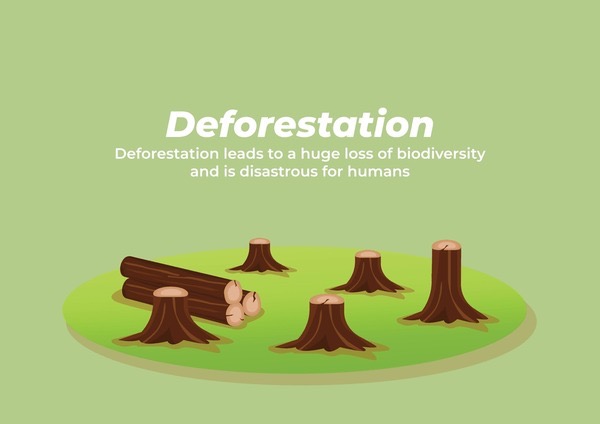
Sejak 25 November 2025, banjir bandang dan tanah longsor yang melumpuhkan Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat menyingkap tabir ketidakadilan iklim yang selama ini belum terbuka. Menurut data BNPB bencana Sumatera per 3 November 2025 telah menelan 770 korban jiwa dan 443 orang masih dalam pencarian. Tragedi ini tidak lagi dapat dipandang sebagai bencana alam yang tidak terduga. Bencana di Sumatera mencerminkan krisis yang lebih mendasar, yaitu kerusakan tata kelola lingkungan dan ketidakadilan iklim yang selama ini dibiarkan menumpuk.
Sumatera tidak hanya menjadi rumah bagi sebagian kawasan hutan tersisa di Indonesia, tetapi juga menjadi salah satu wilayah dengan beban ekologis paling berat. Ekspansi sawit, tambang batu bara, dan konsesi hutan tanaman industri berlangsung dalam skala masif selama bertahun-tahun. Data menunjukkan bahwa wilayah Sumatera kini dikelilingi oleh ribuan aktivitas ekstraktif: terdapat 1.907 izin tambang yang masih aktif dan kawasan konsesi yang jika digabungkan mencakup sekitar 2,4 juta hektare, belum termasuk berbagai izin pemanfaatan hutan.
Masalahnya, beban ekologis ini tidak ditanggung secara adil. Masyarakat lokal yang tidak mendapat keuntungan berarti dari ekspansi ekonomi ekstraktif justru menanggung risiko terbesar. Mereka kehilangan kebun, rumah, dan mata pencaharian ketika banjir atau longsor datang. Mereka menghirup asap ketika kebakaran hutan terjadi. Sementara keuntungan utama dari ekspansi perkebunan, tambang, dan industri energi justru berpusat pada korporasi dan pemerintah pusat. Di sinilah ketimpangan keadilan iklim terlihat jelas: mereka yang paling sedikit menyumbang kerusakan justru menjadi pihak yang paling menderita.
Keadilan iklim menuntut agar risiko dan manfaat terbagi secara proporsional. Namun hal tersebut tidak tampak dari temuan data di Aceh berikut: Untuk wilayah Aceh, total kerugian yang dicatat mencapai 2,04 triliun rupiah (Celios, 2025). Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan penerimaan daerah dari sektor yang selama ini dikaitkan dengan tekanan ekologis. Penerimaan negara bukan pajak dari pertambangan di Aceh hingga akhir Agustus 2025 hanya berjumlah 929 miliar rupiah. Dana Bagi Hasil dari perkebunan sawit yang diterima Aceh pada tahun yang sama hanya 12 miliar rupiah dan DBH dari sektor minerba hanya 56,3 miliar rupiah (Detik, 2025). Besaran penerimaan tersebut tidak mendekati nilai kerugian akibat banjir yang mencapai lebih dari dua triliun rupiah.
Pemerintah daerah yang memiliki APBD terbatas kesulitan membiayai restorasi ekosistem, membangun infrastruktur mitigasi, atau memberikan perlindungan sosial yang memadai. Ketika bencana datang, daerah harus menanggung biaya pemulihan, meski mereka bukan pihak yang menyebabkan kerusakan ekologis sejak awal. Dalam konteks ini, ketidakadilan fiskal menjadi lapisan tambahan dari ketimpangan ekologi.
Perencanaan pembangunan yang tidak hati-hati dan kelonggaran pengawasan juga turut memperburuk keadaan. Tata ruang yang tidak ketat memungkinkan konsesi diberikan di wilayah rawan bencana. Pengawasan izin sering lemah, sehingga praktik perusakan lingkungan dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa konsekuensi berarti.
Selain itu di tingkat pusat dan daerah, kebijakan mitigasi dan adaptasi belum terhubung dengan baik. Instrumen pendanaan hijau seperti transfer fiskal berbasis ekologi (EFT) belum diterapkan secara merata di tingkat nasional, padahal mekanisme ini dapat memberi insentif bagi daerah yang menjaga hutan dan sumber daya air. Tanpa dukungan pendanaan yang kuat, sulit bagi daerah untuk keluar dari lingkaran bencana yang berulang.
Untuk mengubah situasi ini, pendekatan yang diambil tidak bisa lagi bersifat tambal sulam. Sumatera membutuhkan kerangka keadilan iklim yang konkret: pendanaan ekologis yang memadai, penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas ekstraktif merusak, dan pemulihan ekosistem serta hutan yang rusak. Keadilan iklim bagi masyarakat lokal harus menjadi prioritas, bukan efek samping dari agenda ekonomi. Pendekatan adaptasi dan mitigasi harus berakar pada komunitas, bukan hanya pada kebijakan makro yang sering tidak menyentuh akar persoalan.
Pada akhirnya, bencana yang menghantam Sumatera kali ini adalah cermin dari bagaimana ketidakadilan iklim bekerja di tingkat daerah. Bagaimana eksploitasi sumber daya dianggap wajar dan biaya sosial-ekologisnya ditanggung langsung oleh masyarakat. Sumatera membutuhkan kebijakan yang mengakui beban ekologis yang telah dipikulnya, sekaligus memastikan bahwa risiko dan tanggung jawab ditata ulang secara adil. Keadilan iklim bukan slogan; ia adalah syarat agar Sumatera dapat keluar dari krisis bencana yang berpotensi berulang.
Penulis: Zinedine Reza
